*Dimuat di Majalah Kartini Edisi November 2018 – Januari 2019
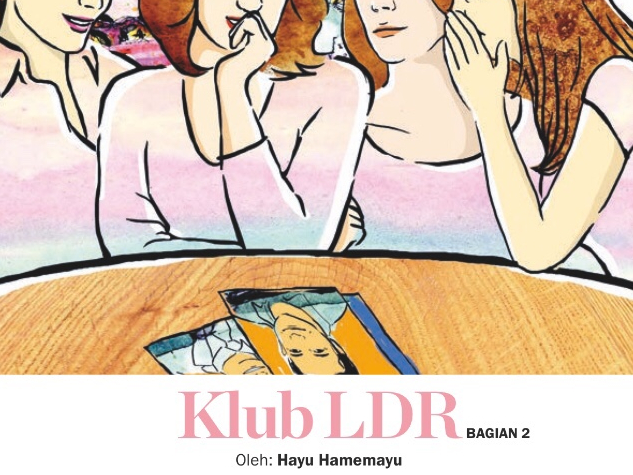
“Trtttt…trrrr…trtttt” ponselku bergetar di atas meja.
Aku tersentak bangun dari tidurku dan meraba-raba meja untuk meraihnya.
“Halo? Nes?” suara Yan terdengar dari seberang.
“Whoammmm, ya?” jawabku dengan suara serak.
Mata sepatku melirik ke arah jam di dinding. Pukul 12.20 dini hari. Aku dan Yan memang punya janji telepon malam ini. Dan karena Yan baru pulang dari kampusnya pukul 18.00 waktu Swedia, yang berarti tengah malam di sini, akupun jatuh ketiduran saat menunggu telponnya.
“Ngantuk ya, sayang?” tanya Yan klise.
Aku cemberut meski Yan tak bisa melihatku. Tentu saja aku ngantuk. Ini sudah lewat tengah malam.
“Enggak kok,” kataku berbohong.
Lalu kamipun tenggelam dalam obrolan tentang aktivitas kami seharian ini.
Sejak Yan berangkat ke Stockholm tiga bulan lalu, hampir setiap hari kami bertukar kabar lewat telepon, video call, atau minimal saling mengirimi pesan. Berkat teknologi, jarak memang jadi “terasa” lebih dekat. Dibandingkan LDR-LDRku sebelumnya, LDR kali ini bisa dibilang lebih tertata. Tapi tetap saja, perbedaan waktu membuat kami berdua kewalahan. Aku jadi sering bangun lebih siang karena harus melakukan panggilan rutin ke Yan tengah malamnya. Pagiku juga jadi selalu buru-buru. Tak bisa lagi kunikmati kopi pagiku dengan santai dan berangkat kerja tanpa kuatir ketinggalan kereta.
Tapi aku tak bisa menyalahkan siapapun. Kondisi ini berat bagiku maupun Yan. Dan dengan beban Yan yang kuliah sambil bekerja di kampus karena sistem S3 di Swedia menuntutnya begitu, aku tak punya hati untuk merajuk. Kami sudah pernah mencoba mengganti jadwal telepon kami ke pagi hari waktu Swedia. Tapi susah bagiku untuk menerima telepon saat jeda makan siang. Belum rapat kantor yang bisa molor sewaktu-waktu. Jadwalku sendiri tak selalu jelas waktu istirahatnya. Akhirnya kami kembali ke pengaturan awal. Telepon di malam hari. Panggilan video di akhir pekan. Pesan di waktu-waktu yang tidak perlu ditentukan.
Selain mengobrol dengan teman-teman di kantor, hiburanku di masa LDR ini adalah bertemu dengan para anggota Klub LDR. Lima orang yang tadinya asing tersebut kini telah menjadi sahabat-sahabat baikku. Yang selalu bisa menghiburku dengan caranya masing-masing. Misal pernah suatu kali aku datang ke pertemuan kami dengan tampang awut-awutan karena kurang tidur. Bu Kas langsung memesankan kopi favoritku tanpa kuminta. Dan Tik langsung menepuk-nepuk punggungku sambil bilang: “Be strong, girl! Kami semua ngerasain yang kamu rasain,”
“Thanks! Kita pasti bisa,” kataku sambil mengepalkan tangan.
“Lagipula, siapa sih yang belum pernah LDR? Ki Hajar Dewantara saja pernah,” tambahku sok bijaksana.
“Oh ya?” tanya Rum polos.
“Makanya baca Rum, jangan stalking instagram artis doang,” timpal Tik ketus membuat Rum manyun.
Selain mereka, aku juga jadi berteman dengan Bas, si barista yang kusapa di hari pertama pertemuan Klub LDR. Kunjungan rutinku ke Simply Coffee membuat kami jadi sering bertemu. Dan karena seringnya aku yang datang paling awal, aku jadi terbiasa mengobrol dengan Bas lebih dulu. Bas juga kadang nimbrung sebentar kalau kafe sedang sepi. Sekedar basa-basi atau bertanya soal kelanjutan LDR kami masing-masing. Dia tak ubahnya anggota tambahan tidak tetap Klub LDR. Rum yang paling sumringah setiap kali Bas mendekati sudut tempat kami duduk. Senyumnya merekah dan matanya berbinar seperti remaja bertemu artis idola. Wajar sih, Bas memang ganteng.
Bulan demi bulan berlalu tanpa halangan yang berarti selain soal panggilan tengah malam dan pagi yang berantakan. Selebihnya, hubunganku dan Yan bisa dibilang baik-baik saja. Bahkan, tahu-tahu, ini sudah Mei. Yang artinya, dua bulan lagi Yan akan pulang. Dua bulan lagi aku bisa memeluk kekasihku itu. Kalender di kamarku sudah kulingkari besar-besar dengan spidol warna merah. Aku benar-benar tak sabar ingin segera bertemu Yan. Tidak di kantor, tidak di pertemuan Klub LDR, aku terus-terusan digoda karena cengar-cengir kegirangan menunggu Juli tiba.
Hingga satu malam, saat kami sedang melakukan panggilan telepon seperti biasa, nada bicara Yan tiba-tiba berubah.
“Nes, aku mau ngomong sesuatu,” kata Yan pelan.
“Ya, ngomong aja. Kan dari tadi kita juga sudah ngomong,” kataku bercanda.
“Ehm, sorry ya Nes, aku enggak jadi pulang Juli nanti. Libur musim panas ini ada summer school di Milan dan supervisorku bilang, sebaiknya aku ikut. Maaf ya, sayang. Kayaknya aku baru bisa pulang pas libur musim dingin nanti,” jelas Yan. Nada bicaranya terdengar hati-hati, seolah takut menyakitiku.
Aku tak langsung merespons. Lututku mendadak lemas. Rasanya seperti kamu sedang lari maraton dan sudah melihat garis finis tapi kemudian sesuatu menghalangi langkahmu dan mendorongmu mundur jauh ke belakang.
Enggak jadi pulang? Musim dingin nanti? Delapan bulan lagi? Hanya kata-kata itu yang diputar terus-terusan di otakku.
“Nes … kamu baik-baik saja, kan?” tanya Yan khawatir.
Aku ingin berteriak tentu saja aku tidak baik-baik saja. Apa Yan tidak tahu seberapa kangen aku padanya. Apa dia tak kangen padaku? Tapi aku hanya diam saja. Terlalu sedih dan putus asa untuk bicara.
“Sorry banget, Nes,” tambah Yan.
Tak ada satupun dari kami yang bicara untuk beberapa saat. Hanya helaan nafas berat kami yang tumpang tindih satu sama lain. Ada banyak hal yang kupikirkan saat itu. Aku merasa punya hak untuk marah. Tapi adilkah ini semua buat Yan? Semua ini toh bukan keputusannya sepihak. Bukan salahnya kalau supervisornya memintanya ikut kelas musim panas dan bukannya pulang ke Indonesia. Bukan salahnya kalau studi doktoral ini begitu menyita waktu. Mungkin aku hanya perlu bersabar. Sedikit lagi.
“Tapi janji, Desember nanti kamu pasti pulang?” kataku akhirnya setelah berhasil menenangkan diri.
Yan menghela nafas lega mendengar suaraku lagi.
“Iya, aku janji. Makasih ya, Nes. I love you! So so much,” jawab Yan.
Saat itu aku tersenyum. Setidaknya delapan bulan lagi, aku bisa bertemu Yan.
“I love you too,” balasku.
…
“What? Enggak jadi pulang? Tega ih,” teriak Rum saat aku menceritakan telepon Yan malam sebelumnya di pertemuan Klub LDR.
“Tapi kamu enggak apa-apa kan, Nes?” tanya Bu Kas memastikan.
“Saya baik-baik saja, Bu. Sedih sih, tapi saya paham kondisi Yan. Lagipula dia janji akan pulang Desember nanti,” jawabku.
Bu Kas memberikan senyum seolah bangga padaku.
“Kamu sendiri gimana, Rum? Pacarmu jadi datang?” tanyaku pada Rum, mengalihkan fokus klub dariku. Rum memang sempat menyebut beberapa waktu lalu bahwa pacarnya akan pulang sebentar lagi.
“Jadi dong, jangan iri yak, hihi,” kata Rum iseng.
Aku hanya mencibir sementara Tik mendorong bahu Rum sebal. Tik dan Rum memang bisa dibilang tak pernah akur karena sifat mereka yang bertolak-belakang. Tapi aku tahu sebenarnya mereka peduli satu sama lain. Tik terutama. Dia sering tampak khawatir pada sikap Rum yang terlalu cuek.
Bu Kas dan Mbak Im pamit pulang duluan tak lama setelah itu. Mereka harus berbelanja sesuatu untuk menyambut suami Bu Kas yang juga akan pulang akhir bulan ini. Tinggal aku, Tik dan Rum saja yang masih bertahan di Simply Coffee. Tapi Rum tampak asyik dengan dunianya sendiri. Maklum, dia sedang asyik bertukar pesan instan dengan pacarnya.
“Kamu bener baik-baik saja?” tanya Tik tiba-tiba.
“Maksudmu? Tentu saja aku baik-baik saja,” jawabku sambil tertawa.
“Well, you can lie to Bu Kas, not to me,” kata Tik penuh selidik.
Aku mendengus. Setengah sebal karena merasa Tik sedang menginterogasiku. Tapi entah mengapa aku merasa Tik ada benarnya.
“Aku … aku berusaha untuk baik-baik saja,” kataku akhirnya.
Dan dengan kalimat itu tiba-tiba ada beban yang seperti terangkat dari pundakku. Mungkinkah Tik benar? Mungkinkah aku cuma berpura-pura bahwa aku baik-baik saja?
“Menurutku penting buatmu untuk jujur sama dirimu sendiri, Nes. Terutama justru pada dirimu sendiri, dan pasanganmu,” saran Tik.
“Kalau memang kamu keberatan dengan fakta bahwa Yan menunda kepulangannya, sampaikan itu padanya. Bukan untuk mengubah keputusannya, tapi untuk membuatnya tahu apa yang benar-benar kamu rasakan. Trust me, it IS very important,” tambah Tik panjang lebar.
Aku seperti disentak kesadaran baru. Selama ini, entah mengapa aku selalu merasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan-kegagalan LDRku di masa lalu. Dan jauh di dalam hati, aku takut akan mengalami kegagalan itu lagi dengan Yan. Sehingga sekarang, secara tak sadar aku selalu menekan semua kekhawatiranku. Membohongi perasaanku sendiri dan berkompromi sepenuhnya. Aku hanya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Terlalu menuntut ini-itu pada pasangan LDRku.
“Dan ngomong-ngomong, kamu harus hati-hati dengan Bas. He’s really into you. Selama kita ngobrol tadi setidaknya dia sudah melirik ke arahmu empat kali,” kata Tik sambil tersenyum geli.
“Jangan ngaco ah, Tik,” kataku. Tapi aku tak bisa mengendalikan rona merah yang mendadak muncul di wajahku.
“Kalian ngomongin apa sih?” tanya Rum yang langsung nimbrung begitu saja. Rupanya dia sudah selesai dengan pesan-pesan cintanya yang aku yakin pasti penuh emoji hati.
“Nothing important. Yuk ah kita pulang,” kataku segera.
Kalimat Tik tentang Bas barusan membuatku sedikit tak nyaman untuk berlama-lama di Simply Coffee. Benarkah Bas memperhatikanku? Benarkah Bas menyukaiku? Aku berusaha menyingkirkan pertanyaan-pertanyaan itu dari pikiranku dengan bergegas menuju pintu keluar.
“Bye, Bas,” kali ini Rum yang menyapa si barista, sementara aku tak berani melihat ke arahnya. Kalau memang benar yang dibilang Tik, aku harus hati-hati pada Bas.
Sabtu adalah hari yang paling kutunggu-tunggu dalam seminggu. Karena di hari Sabtulah aku melakukan panggilan video dengan Yan. Sabtu adalah hari di mana kami bisa mengobrol berdua dengan hangat sambil melihat wajah masing-masing. Sabtu adalah waktu spesial untuk kami berdua. Hanya aku dan Yan. Tapi Sabtu itu, bukannya Yan, justru wajah seorang perempuan bule tak kukenal yang muncul di layar saat aku menelpon.
“Yannnnn, it’s on,” teriak perempuan itu.
Aku hanya melongo.
“Hi Nes, I heard a lot about you. Yan is in the kitchen now but he’ll be here soon,” kata perempuan yang kemudian kutahu bernama Ann, teman satu ruangan Yan di kampus.
“Hi,” balasku dengan tampang kebingungan.
“Hi honey. Sorry tadi lagi ngambil sesuatu di dapur. How was your week, sayang?” kata Yan ringan seolah tidak ada yang aneh dengan kejadian barusan.
“Oh, she’s cute, Yan!” tambah Ann.
“Thanks, I think,” jawabku, masih mencoba mencerna semuanya.
Meski dalam hati aku tak suka dibilang cute. Please deh, cute is for teenager. I’m an adult.
Setelah saling berkenalan dan berbasa-basi sebentar, Ann pamit. Meninggalkan kami berdua saja. Memang sudah begitu seharusnya. Ini kan hariku dan Yan.
“Kamu enggak ngerasa tadi itu aneh?” kataku tajam begitu Ann pergi.
Jujur aku merasa cemburu pada Ann. Mereka teman satu ruangan. Mereka bertemu hampir setiap hari. Dan nama mereka saja berima: Ann dan Yan. Jangan-jangan … kepalaku pening dijejali berbagai kemungkinan.
Tapi Yan hanya tertawa. Menurutnya kedatangan Ann pagi itu tidaklah aneh. Ann sedang jogging dan melewati area apartemen Yan. Lalu dia bertanya apakah Ann bisa mampir sebentar untuk meminta kopi Indonesia yang dijanjikan Yan tempo hari. Yang tentu saja Yan iyakan. Tapi tepat saat Yan baru saja mau mengambil kopinya di dapur, panggilan videoku masuk. Dan Yan meminta Ann menerimanya lebih dulu karena tak mau membuatku menunggu.
Penjelasan Yan terdengar masuk akal, tapi aku masih bisa merasakan sisa-sisa api cemburu di dadaku. Aku tetap tak suka Yan dekat dengan perempuan lain. Apapun alasannya.
“Jangan berpikir yang enggak-enggak, Nes. You know me,” kata Yan mencoba menenangkanku.
Iya, aku tahu aku kenal Yan. Dan susah memang membayangkan dia selingkuh. Maksudku, Yan bukan jenis laki-laki seperti itu. Selama ini dia sudah cukup membuktikan komitmen dan kesungguhannya padaku. Tapi kalau sedang berjauhan begini, wajar kan kalau aku khawatir?
Jarak kadang membuat hal-hal yang tadinya bukan masalah menjadi tampak seperti masalah. Jarak juga bisa menjebakmu untuk membandingkan. Melihat dan memperhatikan apa yang tidak dimiliki oleh pasanganmu yang kini tampak jelas dimiliki oleh orang lain. Kehadiran dan ketersediaan waktu misalnya.
Aku teringat nasehat Tik tentang bersikap jujur. Maka akupun memutuskan untuk jujur pada Yan tentang perasaanku.
“Aku percaya kamu, Yan. Tapi aku berhak untuk khawatir, kan? Jadi tolong, jaga jarak untukku, ya,” kataku padanya.
Yan tersenyum dan mengangguk mantab.
“Pasti,” tegasnya.
(Bersambung)
Leave a comment